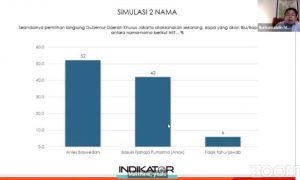Nusantarakini.com, Jakarta –
Tulisan ini akan berusaha mengupas tentang perjalanan spiritual seorang mu’allaf dari keturunan Tionghoa. Beliau telah menorehkan dalam catatannya supaya bisa memberikan hikmah bagi kita semua, khususnya umat Islam dan yang merasa tertarik untuk mengikuti jejaknya.
Rencananya tulisan ini akan dibuat secara bersambung, karena kalau ditayangkan sekaligus akan terlalu panjang. Berikut kisahnya:
———-
MENGETUK PINTU HIDAYAH (1)
Sebagaimana saya dilahirkan di kota dengan banyak komunitas orang Cina yakni Kota Pontianak. Tentunya pergaulan juga banyak dengan kalangan kami sendiri yang mayoritas adalah Budha Khong Hu Cu. Dikatakan demikian karena praktek keseharian adalah Khong Hu Cu yang menyembah Para Dewa. Tapi Khong Hu Cu saat itu belum diakui sebagai salah satu agama yang resmi, sehingga karena takut dikatakan tidak beragama, maka di KTP dicantumkan sebagai penganut agama Budha.
Saya termasuk yang lumayan taat, siang dan sore selalu menyalakan Hio (dupa) sebagai tanda bakti pada Para Dewa.

Saya terlahir dari keluarga yang cukup sederhana dengan nama Lay Fong Fie. Teman-teman biasa memanggil Afong atau Fong Ku. Saya merupakan putera ketiga. Kakak pertama saya laki-laki dan kakak kedua perempuan.
Ketika saya kecil, orang tua sempat berpisah selama 7 tahun. Kakak sulung ikut bapak, kakak perempuan dan saya ikut ibu. Hal ini terjadi karena ibu saya terjebak menanggung utang adiknya. Kronologisnya yaitu keluarga ibu disuruh bikin arisan, dan keluarga ibu sebagian besar ikut terus “piau” (pasang tinggi) dan dapat semua. Ketika mau bayar, ibu saya yang tanggung. Sehingga sering rumah kami didatangi oleh anggota arisan. Bapakku malu dan marah, terus pergi membawa kakak yang laki-laki. Tinggallah kami bertiga di rumah.
Sejak pisah dengan bapak, ibuku terpaksa banting tulang berjualan keliling dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Setiap hari, makanan yang dijual bergantian, seperti kolak, bubur ketan hitam, keladi kukus, sampai gudeg kuah. Sekali jalan membawa untuk berjualan bisa diatas 5 kg. Beliau berjalan sampai berkilo-kilo meter. Tentunya capek dan lelah sekali. Tetapi ibuku tabah. Belum pernah saya mendengar beliau meratapi nasib kami, belum pernah menangis karena itu.
Belum lagi tekanan dari tetangga dan peserta arisan yang menagih terus. Ibuku selalu tertunduk ketika dicaci maki. Mungkin malu dan sedih. Untung beliau masih kuat bertahan membesarkan kami berdua.
Ketika kisah ini saya ketik tanpa terasa air mata mengalir membayangkan penderitaan batin ibuku, yang waktu itu belum terpikirkan karena masih kecil. Harapan kami bertiga adalah bisa berkumpul kembali dengan bapak dan kakak laki-laki. Tetapi kami tidak tahu bagaimana caranya.
Ketika hujan lebat dibarengi guntur menggelepar, ibuku sedang berjualan, kami selalu ketakutan. Kami sedih ketika ibuku pulang sementara jualannya masih banyak tersisa karena hujan. Tidak ada yang peduli. Kami ingin menceritakan, tapi suara kami tidak ada yang mendengar…..Kami pasrah……[mrm]
BERSAMBUNG….
*Ustadz Abdul Hadi (Lay Fong Fie), sekarang mengelola Yayasan Hikmah Sejati di Yogyakarta.
Selengkapnya
- Kisah Muallaf bagian 1
- Kisah Muallaf bagian 2
- Kisah Muallaf bagian 3
- Kisah Muallaf bagian 4
- Kisah Muallaf bagian 5
- Kisah Muallaf bagian 6
- Kisah Muallaf bagian 7
- Kisah Muallaf bagian 8
- Kisah Muallaf bagian 9
- Kisah Muallaf bagian 10
- Kisah Muallaf bagian 11
- Kisah Muallaf bagian 12
- Kisah Muallaf bagian 13
- Kisah Muallaf bagian 14