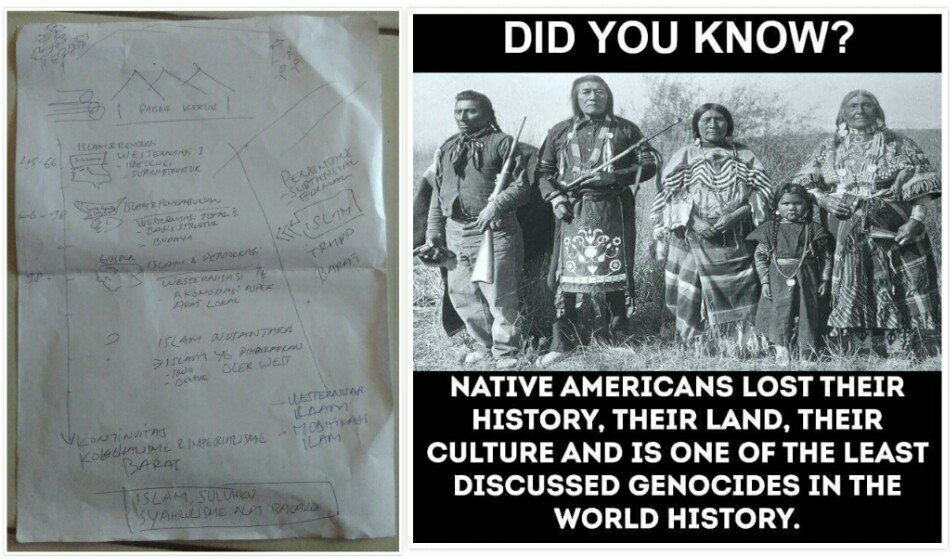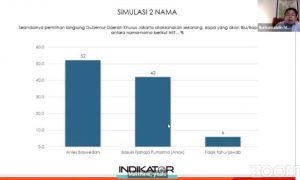Nusantarakini.com, Jakarta –
Aku membaca sebuah laporan lama. Tentang sebuah pabrik raksasa bubur kertas di pedalaman Filipina. Di zaman Ferdinand Marcos. Presiden Filipina yang digulingkan rakyat. Begini ceritanya.
Zaman itu, zaman pembangunan. Zaman modernisasi. Sama seperti Indonesia. Watak kekuasaan politiknya sama. Militer digerek berkuasa. Menjadi agen kapitalisme global. Penjadi jongos Barat, menghisap dan menghabisi SDA negaranya sendiri. Diatur dan diorkestra oleh Bank Dunia dan IMF. Penikmat keuntungannya, para kapitalis global. Seperti keluarga Rothschild, Rockefeller, dan sejenisnya.
Sayangnya, ketika rezim diktator perusak itu runtuh, institusi bank dunia, IMF, dan kapitalis-kapitalis globalnya, tetap tak disalahkan. Padahal mereka adalah perancangnya.
Ok. Kembali ke awal. Nama pabrik bubur kertasnya ialah Cellophill Resource Corporations.
Pabrik ini mengingatkan kita ke pabrik bubur kertas di Indonesia. Ada dua di Riau. Ada juga di Kalimantan. Kenapa pabrik bubur kertas yang padat modal harus hadir? Apa hubungannya dengan tulisan ini?

Mari kita belajar dari pabrik Cellophill itu. Pabrik ini alat untuk menambang keuntungan secara besar-besaran dan sistematis. Tapi merusak ekosistem dan ruang hidup masyarakat lokal.
Ketika pabrik ini hadir, dia meminta bahan baku yang sangat besar. Bahan bakunya dari alam. Yaitu pohon yang tersedia lama di hutan. Masalahnya, hutan itu tempat warga menggantungkan hidup. Di situ terdapat sungai. Di sungai itu tersedia ikan-ikan sebagai sumber hewani dan protein bagi penduduk. Di hutan itu, sumber makanan dan obat-obatan dapat dipanen setiap kali dibutuhkan. Pendeknyaya, hutan itu adalah sumber rezeki. Karena penduduk hidupnya dengan menggantungkan pada alam.
Mereka bukan seperti masyarakat yang ekonominya berdasarkan uang dan hidup dari gaji dan nilai tambah. Sistem ekonomi mereka ialah swadaya, swasembada dan food gathering. Mengumpulkan sumberdaya secukupnya, menikmati secukupnya. Tidak ada gejala akumulasi, penumpukan, penghisapan, pemerasan, manipulasi, seperti pada gejala masyarakat barat yang mengaku modern. Salahnya, gejala masyarakat barat ini pulalah yang sedang dipaksakan diadopsi oleh masyarakat pasca kolonial seperti Filipina.
Sadar bahwa ruang hidup mereka terancam oleh aksi korporasi Cellophill yang akan menghabisi isi hutan-hutan mereka, lalu penduduk yang dipandang primitif itu pun melawan. Singkat cerita, setelah menempuh dialog, negosiasi, dan kemudian buntu, maka mereka angkat senjata. Akibatnya, aksi pembabatan hutan terganggu. Tapi, rezim Marcos turun mengamankan kelangsungan korporasi. Karena dia yakin, dengan kehadiran korporasi di wilayah penduduk pedalaman itu, pembangunan infrastruktur dapat terdongkrak. Seperti jalan raya propinsi, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Pendeknya, korporasi yang lapar hutan itu, diletakkan sebagai katalisator pembangunan. Itulah sebabnya, Marcos berhadapan secara diametral dengan penduduknya sendiri. Dalam hal ini, Marcos telah menjadi jongos dari perusahaan yang dibiayai oleh sindikasi bank asing itu.
Hasil dari kehadiran korporasi Cellophill, ialah mengubah ruang hidup penduduk. Kemudian, berubah pula cara mencari makan penduduk. Tadinya makanan diperoleh langsung dari alam secara bebas, sekarang karena sebagian jadi orang gajian sebagai buruh kasar, maka penduduk hanya bergantung pada uang. Secara sistematis, penduduk dipaksa mengadopsi budaya ekonomi uang. Apa-apa uang. Padahal tadinya, apa-apa, kerja dan cari langsung ke hutan atau ladang. Di titik ini, penduduk telah kehilangan kemerdekaannya sekaligus kehilangan kebahagiaan dan kenyamanannya. Semua itu terjadi secara dipaksa dengan memperalat negara. Negara berhasil mengubah penduduk menjadi setengah budak dan memisahkan penduduk dari kekuasaan lamanya terhadap hutan mereka. Dan negara merampas hak dan kekuasaan atas hutan-hutan dan ruang hidup mereka yang telah lama mereka nikmati, hanya dengan klaim konstitusi dan undang-undang yang diproduksi oleh rezim secara permanen, dan tiba-tiba beralih hak kepada departemen kehutanan, badan pertanahan dan tanda tangan presiden dan menteri. Lantas, apakah sebenarnya negara diciptakan untuk memfasilitasi kelangsungan imperialisme?
Penduduk pun dipaksa dialihkan pengeksploitasiannya kepada perusahaan yang hadir atas fasilitasi negara.
Jadi, ini adalah imperialisme yang cerdik dan sistematis. Yang penting, surplus tetap mengalir ke para kapitalis asing. Sumberdaya alam dan tenaga manusia Filipina dengan lancar dan aman dapat dieksplorasi dan dieksploitasi. Persis sama dengan kasus Indonesia, bukan?
Pemerintah dan aparatnya diperkuda sebagai alat penjamin bagi hadirnya kapital. Alam dan penduduknya diperas untuk menghasilkan surplus dengan harga murah. Judulnya, demi pembangunan. Musibah yang ditanggung, rusaknya lingkungan, hilangnya kebebasan mencari rezeki, bertukar menjadi rezeki yang diatur oleh manusia kolonialis, walaupun kulitnya sawo matang.
Budaya penduduk pun dimodifikasi agar sesuai tuntutan dan selera para pengambil keuntungan dari proyek pembangunan. Hingga waktu berlalu, penduduk pun terasing dari budaya awal dan aslinya. Mereka tersendat-sendat dan terhuyung-huyung menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan sosial baru yang diciptakan oleh penjajah dan komparador rezim binaannya seperti Marcos dan Soeharto.
Demikianlah, sebenarnya imperialisme tak pernah berhenti dan angkat kaki. Dia tetap hadir dengan gaya dan taktik baru yang lebih tidak kasat mata.
Maka ketika pabrik kertas dan pulp milik Sinar Mas dan RAPP di Riau demikian mengherankan karena demikian besar dan hebatnya, hanya satu yang menjelaskannya sehingga masuk akal: bahwa pabrik semacam itu terkait dengan gejala imperialisme seperti yang telah terjadi di Filipina di tahun 70-an awal yang kemudian menimbulkan perlawanan dari penduduk setempat. Pertanyaannya, kenapa Riau dapat berhasil dipasifikasi oleh rezim Soeharto hingga hari ini, dan kenapa Filipina, tidak? Barangkali ada karakter lahan yang berbeda antara di pedalaman Filipina dan di Riau. Boleh jadi?
~ Syahrul E Dasopang