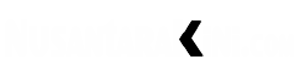Bahasa Asing Bernama Kekuasaan: Esai Reflektif tentang Jarak Rakyat dan Bangsa

“Kalian bertengkar ramai dalam bahasa yang bagiku sama asingnya dengan bahasa nasib manusia.”
— Jejak Langkah, Pramoedya Ananta Toer, 1985.
Nusantarakini.com, Surabaya –
Begitu riuh para elite berdebat—tentang sistem, konstitusi, regulasi, indeks ekonomi, bahkan moral. Kata-kata mereka panjang, rumit, dan megah. Tapi bagiku, rakyat kecil di ujung kampung, bahasa mereka tak ubahnya mantra asing: tak kupahami, tak kunikmati, dan tak pernah menyentuh nasibku. Mereka saling serang di podium, saling koreksi di televisi, tapi dapurku tetap kosong, harga tetap naik, dan tanah tetap dicaplok.
Bahasa mereka bukan bahasa rakyat. Mereka tidak sedang bicara demi perubahan, mereka sedang melanggengkan posisi. Bahasa kekuasaan selalu punya dialek sendiri—penuh retorika, minim empati.
Dan di sinilah aku mengamati:
Aksi dan reaksi sekolah-sekolah fikiran—entah liberal, konservatif, sosialis, atau teknokrat—telah menjadi arena adu gagasan tanpa ujung. Tapi semua itu hanya berarti jika mampu menentukan keberlangsungan hidup bernegara. Kalau tidak, itu hanya debat elit yang menjauh dari denyut rakyat.
Apa gunanya ideologi tanpa pangan? Apa gunanya teori negara jika rakyat tak bisa bayar sekolah anaknya? Apa gunanya konstitusi jika hukum hanya tajam ke bawah?
Jika pertarungan intelektual hanya berakhir di seminar, tanpa menyentuh petani dan tukang becak, maka itu bukan kebangkitan—itu masturbasi intelektual.
Di gedung-gedung megah bernama lembaga negara, para elit berseteru dalam bahasa yang tampak intelektual namun kering dari rasa. Mereka berbicara tentang hukum, fiskal, reformasi, indeks demokrasi, inflasi, dan revisi undang-undang. Mereka berdebat dengan penuh semangat, mengutip teori dari Eropa, hukum Romawi, dan konstitusi hasil amandemen.
Namun bagi sebagian besar rakyat, semua itu terdengar seperti denting logam kosong. Retorika canggih itu terasa asing, sejauh bahasa planet lain. Karena bagi mereka, bahasa kehidupan adalah beras yang mahal, anak yang demam tapi tidak dibawa ke puskesmas karena tidak punya BPJS, atau kehilangan tanah karena digusur proyek strategis nasional.
Mereka—para penguasa dan kaum terpelajar—bertengkar dalam bahasa yang asing bagi rakyat. Bukan hanya secara kosa kata, tapi juga secara empati.
Mereka bicara soal “stabilitas ekonomi,” tapi rakyat hanya ingin stabilitas harga minyak goreng.
Mereka bicara soal “pertumbuhan GDP,” tapi rakyat hanya ingin penghasilan yang cukup sebelum tanggal 20.
Mereka bicara soal “pemilu jurdil,” tapi rakyat hanya ingin suaranya didengar tanpa harus menjual KTP.
—
Sekolah Fikiran dan Arah Negeri
Aksi dan reaksi sekolah fikiran—dari sosialis yang idealis hingga kapitalis yang oportunis—saling bertabrakan dalam ruang publik. Mahasiswa saling baku debat, akademisi saling kritik paper, tokoh publik saling nyinyir di media sosial. Semua merasa memegang kebenaran moral dan intelektual. Namun satu pertanyaan yang belum pernah dijawab secara jujur:
Apakah semua ini benar-benar menentukan keberlangsungan hidup rakyat bernegara?
Karena jika tidak, itu semua hanyalah pertunjukan intelektual untuk kalangan sendiri. Seperti debat filsuf di menara gading, yang gemanya tak pernah menyentuh tanah berlumpur tempat petani berjongkok menunggu panen gagal.
Pemikiran tanpa akar realitas hanya akan melayang. Negara pun akan menjadi seperti balon besar—mengambang dalam slogan dan jargon, tapi tidak pernah menginjak bumi.
—
Negara dan Rakyat: Siapa Yang Asing, Siapa Yang Terasing
Jika rakyat merasa asing di negeri sendiri, maka negara telah gagal menjelma sebagai rumah.
Jika rakyat harus menerjemahkan bahasa pemimpinnya sebelum memahami maksudnya, maka itu bukan komunikasi, itu penjajahan simbolik.
Jika rakyat harus dituduh bodoh setiap kali mempertanyakan kebijakan, maka itu bukan pendidikan politik, itu penghakiman kultural.
Bahasa rakyat adalah bahasa luka. Bahasa lapar. Bahasa kecewa. Bahasa yang tidak butuh definisi akademik, tapi pengakuan. Tapi sayang, mereka yang duduk di atas, lupa bahwa rakyat bukan hanya objek statistik, tetapi subjek sejarah.
Negara ini terlalu sering membungkam jeritan dengan laporan, menyulap tangisan dengan grafik, dan mengganti kritik dengan konferensi pers.
—
Penutup: Kembali ke Bahasa Kemanusiaan
Kita tak sedang kekurangan ahli hukum, ekonom, atau filsuf. Kita sedang kekurangan pendengar sejati. Kekurangan pemimpin yang bisa menyederhanakan bahasanya tanpa merendahkan maknanya. Kita kekurangan pejabat yang berbicara dengan hati, bukan dengan catatan pidato dari stafnya.
Sudah saatnya kita kembali menggunakan bahasa yang paling mendasar—bahasa manusia. Bukan bahasa kekuasaan, bukan bahasa pencitraan, bukan bahasa debat politis yang penuh jebakan logika. Tapi bahasa yang membuat seorang ibu bisa percaya bahwa anaknya akan bisa sekolah. Bahasa yang membuat nelayan yakin bahwa laut tidak hanya akan jadi milik investor.
Karena jika negara tidak kembali memahami bahasa rakyatnya, maka rakyat akan menciptakan bahasanya sendiri—dalam bentuk protes, amarah, bahkan pemberontakan.
Dan saat itu terjadi, pertarungan bukan lagi soal diksi, tapi eksistensi. [mc]
*Pak Sayuh, Sopir Trailer Peduli Bangsa.