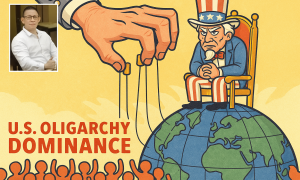Nusantarakini.com, Jakarta –
Karena pengalaman saya selaku konsultan politik, yang sudah tiga kali berturut-turut ikut memenangkan pilpres (2004, 2009, 2014), banyak wartawan, tokoh politik, pengamat bertanya. Bagaimanakah potensi pengkubuan politik menuju 2019? Kubu mana yang akan lebih kuat.
Banyak cara melukiskan polarisasi politik. Yang paling sederhana adalah “follow the centers of political power “: ikuti saja manuver para tokoh politik yang paling berpengaruh. Tapi siapakah tokoh politik yang paling berpengaruh dan apa kriteria berpengaruh itu?
Ada banyak tokoh politik yang berpengaruh saat ini. Namun puncaknya kita hanya melihat ada empat pusat kekuasaan saja. Hanya ada empat “GodFather/GodMother/Patron” dalam politik Indonesia. Mereka menjadi pusat politik karena luasnya jaringan yang mereka bisa gerakkan.
Pertama tentu saja Jokowi. Ini karena ia Presiden RI, yang menjadi komando bagi pemerintahan nasional. Kedua adalah Megawati karena ia ketua umum dan penentu partai terbesar PDIP.
Ketiga adalah SBY karena ia masih aktif dalam politik, ketua umum partai besar Demokrat, dan sepuluh tahun menjadi presiden Indonesia.
Keempat adalah Prabowo karena ia ketua umum Parta Gerindra yang kini elektabilitasnya nomor dua setelah PDIP. Prabowo sendiri tokoh yang elektabilitasnya paling tinggi di luar Jokowi selaku Presiden RI.
Sebenarnya ada kekuatan lain seperti Aburizal Bakri, Luhut Panjaitan, ketua umum Golkar. Namun Aburizal tak lagi sepenuhnya mengontrol Golkar karena ia bukan ketua umum. Luhut Panjaitan kuat bukan karena dirinya sendiri tapi bersumber dari Jokowi. Ketum Golkar Setnov yang juga ketua DPR sedang bermasalah hukum.
Praktis “superstars” dalam politik Indonesia adalah empat tokoh itu: Jokowi, Mega, SBY dan Prabowo
-000-
Problemnya tak semua Pusat kekuatan itu bisa bersinerji karena riwayat masa silam dan kepentingannya.
Sulit melihat Mega dan SBY bersatu dalam kubu politik yang sama. Dua mantan presiden ini sudah lama diketahui seperti “Tom and Jerry” politik Indonesia. Walau orang dekatnya acapkali mencoba mengakurkan keduanya, namun selalu gagal. Sama sulitnya menyatukan Tom and Jerry dalam kisah kartun yang terkenal.
Sementara Jokowi dan Prabowo adalah dua personaliti yang mudah bertemu dan berkomunikasi. Namun kepentingan politik keduanya berseberangan. Yang satu Presiden RI, yang lainnya tokoh yang juga dianggap pendukungnya layak menjadi presiden RI. Celakanya presiden RI hanya untuk satu orang.
Megawati sulit bersatu dengan SBY, tapi mudah bersatu dengan Jokowi atau Prabowo. Bahkan Prabowo adalah calon wakil presiden Megawati pada pilpres 2009. SBY juga sulit bersatu dengan Megawati tapi mudah saja berkubu dengan baik Prabowo atau Jokowi.
Namun kondisi saat ini, karena Mega lebih dahulu dan masih satu kubu dengan Jokowi, tak ada pilihan lain bagi Prabowo dan SBY. Jika SBY dan Prabowo ingin menyaingi kekuatan Jokowi+Mega, SBY dan Prabowo harus pula menyatukan kekuatan.
-000-
Siapakah yang akan lebih kuat di pilpres 2019? Jokowi+Mega atau SBY+Prabowo? Per hari ini, dua poros itu sama punya pesona, kekuatan dan kelemahan.
Jokowi di H-2 tahun (dua tahun sebelum pilpres 2019, untuk jabatannya yang kedua), tak sekuat SBY H-2 tahun (SBY di tahun 2007, 2 tahun sebelum Pilpres 2009 untuk jabatannya yang kedua).
Elektabilitas Jokowi saat ini rata-rata di angka di bawah 45 persen dengan aneka simulasi. Sementara SBY di periode yang sama (2007, ketika masih menjabat presiden, juga 2 tahun sebelum pilpres berikutnya), elektabilitas SBY di atas 55 persen, juga dengan aneka simulasi.
Bagi incumbent, jika dukungan di bawah 50 persen, itu adalah sesuatu. Bahkan Ahok saja selaku incumbent (gubernur Jakarta) yang H-1 tahun dengan dukungan hampir 60 persen bisa tumbang.
Jokowi diuntungkan karena ia masih presiden, masih mengelola kebijakan dan dana APBN. Banyak perbaikan yang masih ia kendalikan.
Namun ada dua hal ini yang Jokowi harus hati-hati. Jika salah mengelola, kekuatan Jokowi akan terus tergerus.
Pertama, kita sebut saja “Ahok Effect.” Ahok yang kinerjanya memuaskan publik Jakarta hingga di atas 70 persen bisa tumbang karena tak pandai mengelola “sentimen Islam” yang merupakan pemilih mayoritas negeri ini. Tak ada tokoh yang bisa tahan jika ia sudah terkena label “negatif terhadap Islam.”
Kita tahu label itu adalah semata persepsi. Tak pernah kita tahu hati tokoh itu yang sebenarnya. Namun jika persepsi publik sudah terbentuk seorang tokoh dianggap “negatif terhadap Islam,” atau “kurang positif terhadap Islam,” badai opini publik segera menimpanya.
Di mata pemilih Islam, persepsi atas Jokowi masih OK. Namun sudah mulai muncul dan sudah dihembuskan persepsi Jokowi yang dianggap “kurang positif” terhadap Islam.
Kasus Perpu pembubaran Ormas, tanpa lewat pengadilan, dikritik oleh aneka tokoh dan lembaga hak asasi manusia yang kredibel. Bahkan Human Right Watch tingkat dunia yang bermarkas di Amerika Serikat ikut mengeritiknya secara keras di koran berpengaruh Washington Post. Korban pertama Perpu itu adalah HTI, ormas Islam pula.
Masalah kedua Jokowi adalah komitmennya pada kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kerelaan menerima kritik sebagai hal tak terelakkan dalam sistem demokrasi.
Di kalangan aktivis dan intelektual yang dulu bahkan mendukung Jokowi mulai menarik jarak. Jokowi dianggap terlalu mudah menangkap aktivis dengan tuduhan makar, tuduhan yang sangat berat, walau kemudian direvisi. Apa iya seorang sipil yang kritis, tak punya partai, tak punya massa, tak punya dukungan pasukan bersenjata, seperti Sri Bintang Pamungkas ditangkap dengan tuduhan makar?
Soal Perpu pembubaran Ormas tanpa pengadilan, soal UU Pemilu yang menggunakan hasil pemilu 2014 sebagai basis penentu pilpres 2019 yang sudah sangat berbeda, menambah list negatif. Kebijakan Jokowi dipertanyakan dari sisi komitmennya meneruskan semangat reformasi 98.
Dua hal di atas (sentimen Islam dan nilai demokrasi) membuat kubu SBY+Prabowo mendapatkan kekuatan ekstra. SBY+Prabowo menguat bukan saja karena keduanya memang punya basis politik yang riel. Merekapun mendapatkan limpahan dari “the angry voters,” pemilih yang marah dengan situasi.
-000-
Baguskah untuk Indonesia polarisasi Jokowi+Mega versus SBY+Prabowo (jika solid)? Jawabnya: bagus dengan syarat.
Demokrasi dibangun dengan prinsip semakin rakyat diberikan banyak pilihan semakin baik. Semakin kekuasaan tersentralisasi di satu kubu semakin buruk. Raja bisa salah. Pemimpin bisa salah. Jika kekuatan di luarnya terlalu lemah untuk mengontrol akan celaka sebuah negeri.
Jika benar SBY+Prabowo menyatukan kekuatannya, rakyat sejak dini, 2 tahun sebelum pilpres sudah diberikan waktu yang cukup soal alternatif. Jokowi pun akan lebih hati-hati membuat kebijakan karena jika ia salah, publik akan semakin menokohkan kubu SBY+Prabowo.
Apa syaratnya agar polarisasi itu bagus untuk Indonesia? Syaratnya adalah Act of Statemanship: sikap negarawan empat tokoh itu. Apapun yang terjadi, kepentingan negara dan kepentingan publik luas, harus selalu didahulukan dengan cara-cara yang dibenarkan hukum nasional dan konstitusi. [mc]
*Denny JA, Konsultan Politik Senior.