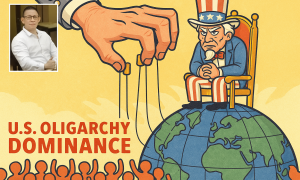Semua Gara-Gara Skincare: Ketika Serum Lebih Kenceng dari Integritas

Nusantarakini.com, Surabaya –
Teryata, Om… semua ini bermula dari skincare. Bukan soal keadilan, bukan soal hukum, tapi soal wajah glowing yang bikin baper. Nikita Mirzani dan Reza Gladis, dua perempuan yang sama-sama suka tampil kinclong, tapi urusan hatinya malah kusam, apalagi di ruang sidang.
Awalnya mungkin hanya sebotol serum, treatment laser, atau suntik anti-aging. Tapi ternyata, efek sampingnya luar biasa: bikin dendam menahun, bikin laporan kepolisian, bahkan bikin keterangan saksi jadi retinol—licin, susah ditangkap, dan bikin mata perih. Rupanya, bukan hanya kulit yang dibersihkan, tapi juga nalar yang ikut terangkat… hilang.
Lucunya, publik melihat dua tokoh ini bukan sedang memperjuangkan kebenaran, tapi sedang adu siapa yang lebih mulus luar dalam. Tapi sayangnya, satu terlalu keras, satunya lagi terlalu tipis. Yang satu berani tampil apa adanya, yang satunya malah berdandan di balik pasal demi pasal.
Dan akhirnya, ketika skincare jadi pangkal perkara, kita semua dipaksa menonton sinetron baru:
“Glow Up Pengadilan: Episode Dendam, Retinol, dan Air Mata.”
Di ruang sidang yang semestinya menjadi arena sakral pengadil kebenaran, kita kembali disuguhkan sebuah drama komedi legal yang layak masuk nominasi Festival Lawak Nasional. Kali ini tokoh utamanya adalah seorang publik figur bernama Nikita Mirzani dan sepasang dokter—Dr. Reza Gladis dan sang suami—yang mendadak tampil tidak sebagai tenaga kesehatan berwibawa, tetapi sebagai saksi kebingungan dengan ekspresi “planga-plongo” yang seolah sedang lupa skrip di panggung sinetron dadakan.
Saksi yang seharusnya menjernihkan perkara, justru tampak seperti orang yang terjebak ujian mendadak, tidak hafal pertanyaan, apalagi jawaban. Miris, karena bukan hanya satu dua kalimat yang tampak janggal, tetapi keseluruhan kronologi yang seharusnya menjadi kunci perkara malah kabur seperti wajah pasca filler gagal.
Konon, isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mereka berbeda jauh dengan keterangan saat di persidangan. Ini bukan pertama kalinya terjadi di republik ini, di mana hukum terasa seperti kulit wajah yang terlalu sering kena suntik: kencang di luar, kosong di dalam. Banyak yang tampak rapi di depan kamera, tapi bolong di nalar dan integritas. Kalau isi BAP bisa berubah-ubah seperti tren alis dan warna bibir, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa keadilan sedang bekerja?
Kecantikan Hukum: Permukaan Menawan, Isi Mengawan
Ironis, seorang dokter kecantikan justru terseret dalam praktik yang merusak estetika hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya lurus, kini jadi bancakan, penuh filler keterangan palsu, suntikan pengaruh, dan perawatan instan untuk menutupi borok keadilan. Kalau begini caranya, hukum kita tak ubahnya wajah penuh perban pasca-operasi plastik—berusaha tampak segar, padahal habis diobrak-abrik.
Publik tidak bodoh. Mereka melihat bagaimana banyak perkara besar bisa berubah arah hanya karena saksi berubah isi cerita. Tapi yang bikin lebih geli, adalah wajah-wajah saksi yang seolah-olah baru bangun tidur, tidak tahu apa-apa, dan menjawab dengan nada tak meyakinkan. Mungkin mereka lebih cocok jadi pasien, bukan dokter.
Dari Klinik Estetika ke Ruang Sidang: Lompatan yang Gagal
Kita maklum, tidak semua dokter dibekali kemampuan logika hukum. Tapi menjadi saksi dalam kasus pemerasan tentu bukan pekerjaan sembarangan. Ada sumpah di sana. Ada tanggung jawab moral. Tapi tampaknya, seperti banyak sektor lain di negeri ini, kejujuran pun kini bisa dimake-up, disesuaikan dengan kebutuhan agenda. Seperti operasi hidung: bisa mancung ke kiri atau ke kanan, tergantung siapa yang membayar.
Sidang ini membuka fakta lucu sekaligus getir. Bahwa dalam banyak kasus, hukum tak ubahnya reality show: yang penting dramanya jalan, rating tinggi, dan para tokohnya tampil penuh gimmick. Persoalan benar dan salah, itu bisa dibicarakan nanti—setelah retouch dan filter.
Planga-Plongo: Simbol Bangsa yang Terbiasa Bisu
Wajah kebingungan Dr. Reza Gladis dan suaminya bukan cuma pantulan dari ketidaksiapan, tapi juga simbol dari sistem yang sudah biasa membiarkan saksi planga-plongo tanpa konsekuensi. Hari ini mereka lupa, besok mungkin ingat lagi, lusa berubah pikiran. Saksi macam begini tidak pantas hadir di ruang keadilan, tapi sangat cocok tampil di acara infotainment atau kuis tebak-tebakan.
Lalu publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya terdakwa dalam kasus ini? Apakah Nikita Mirzani yang dikenal keras, atau sistem hukum yang mulai ringkih, rapuh, dan kehilangan taring?
Sarkasme Penutup: Hukum Kita Butuh Treatment yang Lebih dalam
Jika wajah hukum Indonesia ingin tampil menawan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar serum pencerah, tapi perombakan total dari struktur hingga ke moral. Tidak cukup dengan gincu janji atau BB cream reformasi, tapi butuh pengelupasan mendalam: dari praktik curang, permainan keterangan palsu, hingga saksi pesanan yang siap tampil di panggung manapun asalkan dibayar lunas.
Jika tidak, maka kita akan terus melihat sidang demi sidang seperti ini. Di mana saksi lupa isi BAP, jaksa tersenyum kecut, hakim geleng-geleng kepala, dan publik tertawa getir.
Dan sementara keadilan masih sibuk retouch di belakang panggung, para pencari keadilan hanya bisa berkata:
“Selamat datang di republik planga-plongo, di mana hukum pun butuh make-up.”
Bolehlah orang bebas menghujat Nikita Mirzani—manggilnya Nikmir, si ratu gaduh, ratu bacot, ratu segala keributan di jagat maya. Tapi mari kita jujur, dalam semua kegilaan, setidaknya dia tak pernah lupa menjadi ibu. Mendidik, mengasuh, bahkan pasang badan buat anaknya saat diganggu. Dia boleh gaduh di luar, tapi di dalam rumah dia tetap perisai. Setidaknya, kalau pun mulutnya berapi-api, hatinya masih punya arah. Bukan tipe manusia yang lupa isi pernyataan sendiri di depan hukum.
Bandingkan dengan Reza Gladis dan sang suami. Di satu sisi mereka tampak bersih, rapi, wangi klinik estetika. Tapi di balik tampilan mulus itu, isi kepala dan hati tampaknya perlu disuntik logika. Saat diminta kesaksian, ekspresi keduanya seperti peserta audisi Akademi Pelawak Indonesia yang belum siap skrip. Planga-plongo seolah sedang ditebak, “Apa nama hewan berkaki empat yang suka menggonggong?”
Kebodohan itu bukan dosa. Tapi menjadikan kebodohan sebagai tameng untuk berkelit dari tanggung jawab moral adalah kehinaan intelektual. Ini bukan soal siapa paling glamor atau siapa paling sering naik tayangan gosip. Ini soal keberanian bersikap di hadapan hukum. Dan jika wajah hukum sudah diisi oleh saksi-saksi yang gagap, gugup, dan gagu—maka mungkin sudah waktunya Mahkamah Agung membuka divisi baru: Stand-Up Court Indonesia, karena drama hukum kita semakin lucu dari hari ke hari.
Ada banyak cara mempercantik wajah, tapi tak banyak cara mempercantik integritas. Sayangnya, keduanya sering tertukar. Yang tampil rupawan, dikira berwibawa. Yang berani dan tegas, malah dikira galak tak tahu diri. Tapi dalam pengadilan rakyat, yang planga-plongo adalah lawakan, dan yang tegas justru seringkali jadi harapan.
Maka sebelum hukum benar-benar kehilangan wibawa, mari kita bedakan mana yang pantas di klinik kecantikan dan mana yang layak di ruang sidang. Karena kalau tidak, kelak kita akan melihat para jaksa dan hakim juga ikut-ikutan botox—bukan demi awet muda, tapi agar bisa tersenyum palsu sambil memendam malu.
Kalau kita bicara soal latar belakang, ya jelas jomplang. Reza Gladis dan suaminya itu bergelar akademik, katanya dokter, katanya berpendidikan tinggi, bergaul di lingkaran elite klinik estetik. Sedangkan Nikita Mirzani? Lulusan Universitas Kehidupan. Kampusnya adalah panggung infotainment, dosennya netizen, dan tugas akhir hidupnya adalah bertahan dalam badai fitnah. Tapi anehnya, yang planga-plongo di ruang sidang justru bukan si lulusan jalanan, melainkan para sarjana.
Harusnya, dengan segudang gelar dan pendidikan tinggi itu, Reza dan suami tampil cemerlang di hadapan hukum. Logika tajam, sikap tenang, kronologi runtut. Tapi kenyataannya? Keterangan mereka berubah-ubah seperti tren skincare. Dulu bilang A, sekarang bilang B. Dulu bilang takut diperas, sekarang ketahuan punya dendam pribadi. Lah, ini sidang pemerasan atau forum curhat?
Publik mulai mencium aroma busuk dari balik layar. Bukan aroma keadilan, tapi aroma dendam. Ya, dendam pribadi yang dibalut baju hukum. Seolah pengadilan bisa disulap jadi tempat balas sakit hati. Padahal panggung sidang bukan panggung sinetron. Kalau setiap sakit hati dilimpahkan jadi pasal hukum, maka pengadilan kita akan lebih penuh dari antrean BPJS.
Lucunya, pihak yang katanya terpelajar ini justru mempermalukan diri sendiri. Tidak bisa membedakan mana ranah pribadi, mana urusan hukum. Sedihnya, justru Nikita yang tampil lebih tenang. Dengan segala kontroversinya, dia tetap berdiri tegar. Bukan karena suci, tapi karena dia paham benar medan permainan ini: kalau mau main hukum, mainlah dengan elegan, bukan dengan curhat berkedok dakwaan.
Ah di-gebyah uyah, Om. Mau dibandingkan apel Fuji sama apel lokal, ya tetap harus jelas ukurannya. Kalau si terpelajar saja sudah keblinger, terus siapa yang bisa jadi contoh? Inilah saatnya bangsa ini sadar bahwa pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin moral tinggi. Gelar itu cuma tempelan. Sementara ketegasan, konsistensi, dan keberanian itu datang dari karakter, bukan dari ijazah.
Dan kalau sidang hukum sudah dicampur dengan dendam pribadi, kita bukan sedang menonton persidangan, tapi sedang melihat kompetisi gosip berbalut toga.
Nikita Mirzani tidak butuh pembelaan dariku, setidaknya jika dia baca tulisan ini mungkin dirinya setuju
Firdaus, tokoh dalam novel Women at Point Zero pernah berkata dengan penuh luka dan keberanian:
“Seorang pelacur sukses lebih baik dari orang suci yang sesat.”
Kalimat itu bukan glorifikasi prostitusi, tapi tamparan keras pada kemunafikan sosial. Sebab Firdaus memilih menjual tubuhnya secara sadar, dibanding menjual nurani atas nama kesucian palsu. Ia tahu apa yang ia lakukan, dan tak pura-pura suci. Bandingkan dengan banyak orang terpelajar, bersertifikat, berseragam rapi, tapi dengan mudah menjual harga diri demi reputasi atau dendam pribadi.
Dalam konteks sidang ini, Nikita mungkin dianggap gaduh, keras, bahkan liar. Tapi setidaknya dia tidak munafik. Sementara mereka yang berdiri di balik nama besar, gelar akademik, dan status sosial tinggi—ternyata malah menjadikan pengadilan sebagai arena pelampiasan ego. Di titik ini, pernyataan Firdaus menggema sangat keras: lebih baik jadi orang yang tahu dirinya kotor dan berusaha jujur, daripada tampil suci tapi menebar kebusukan dalam diam.
Dan jika hukum terus diisi oleh orang-orang suci yang sesat, maka jangan heran bila rakyat lebih percaya pada para ‘pendosa’ yang jujur—karena kejujuran jauh lebih langka dari gelar akademik. [mc]
*Pak Sayuh, Sopir Trailer Pecinta Literasi.